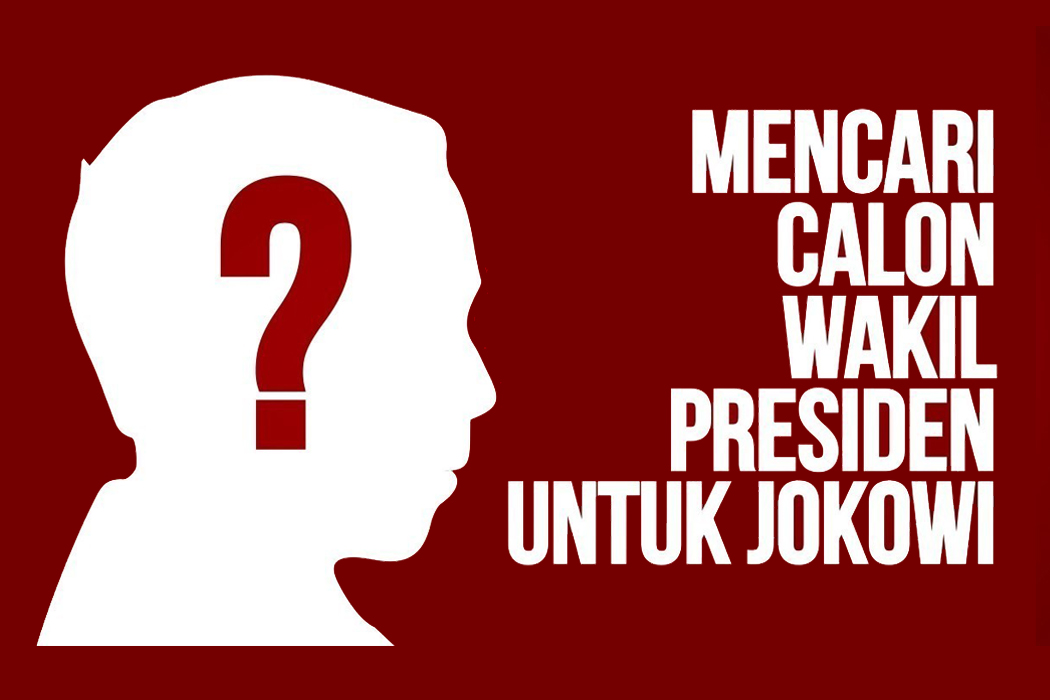
Mencari Cawapres Jokowi
“Tidak. Kami TIDAK MAU jika para kolaborator fasis Jepang itu (Kata Soekarni lantang sambil menunjuk para anggota BPUPKI) ikut menandatangani proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatantanginya Atas Nama Bangsa Indonesia. Karena kami hanya percaya kepada kedua DWITUNGGAL Pemimpin Rakyat ini.” (Ikhtisar Marhaenisme – Pancasila)
Tidak sulit menemukan pasangan. Yang sulit adalah menemukan pasangan yang dirasa pas oleh kita. Mungkin ungkapan ini mewakili Joko Widodo atau siapapun yang tengah menghitung, memilah dan memilih, siapa calon wakil presiden bagi pria yang akrab disapa Jokowi ini. Berbagai kriteria pastinya sangat diperhitungkan oleh mereka. Maklum, ini menyangkut nasib 240 juta lebih rakyat Indonesia. Jika salah pilih, niat mulia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan Negara ini bisa kandas di tengah jalan.
Pertimbangan ini tidak berlebihan mengingat praktik politik kita saat ini memang masih jauh dari ideal. Niatan kerja sama PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang ingin menguatkan kembali presidensialisme, memerlukan kecermatan dalam memilih pendamping Jokowi. Sebab jika salah, alih-alih menguatkan pemerintahan, yang ada malah rongrongan atau tarik ulur politik kembali.
Dengan melihat peluang, dinamika politik, tantangan, serta tujuan memperbaiki kehidupan bangsa dan Negara saat ini, kiranya kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh Jokowi untuk mendampinginya sebagai capres?
Tiga usulan
Beberapa pihak berpandangan Jokowi butuh pendamping yang kuat dalam diplomasi internasional. Pandangan ini berangkat dari lemahnya soal kedaulatan negara beberapa tahun terakhir. Indonesia yang begitu strategis secara geografis, ternyata lemah dalam hal diplomasi, pertahanan, dan kedaulatan.
Beberapa kasus mutakhir misalnya, perkara penamaan KRI Usman Harun yang diprotes Singapura, kasus penyadapan terhadap presiden dan pejabat Negara lainnya, hingga persoalan geopolitik yang lebih luas menyangkut pangkalan militer AS di Darwin. Berangkat dari pandangan ini maka komposisi sipil-militer dipandang sahih dibutuhkan. Kalangan militer dinilai lebih mampu memetakan langkah strategis dalam hal pertahanan. Maka cawapres dari kalangan militer pun mulai didengungkan.
Akan tetapi, ini adalah argumen yang dipaksakan. Jika kita evaluasi 10 tahun pemerintahan SBY yang notebene adalah purnawirawan TNI, ternyata posisi tawar Indonesia dalam hal diplomasi dan pertahanan, serta kedaulatan di perbatasan sesungguhnya tidak jauh berbeda ketika Indonesia dipimpin oleh presiden sipil. Bahkan Gus Dur dinilai lebih piawai dan mampu berdiplomasi di tataran internasional dibanding pemerintahan terakhir. Apalagi jika kita menengok kembali jaman Soekarno, pandangan di atas terbantahkan sama sekali.
Sebagian yang lain melihat Jokowi butuh pendamping dari kalangan teknokrat. Tantangan ekonomi ke depan, agenda pembangunan dan pemerataan, menjadi basis argumentasinya. Selain itu, pasangan dari kalangan teknokrat dinilai akan menjadi faktor penguat Jokowi sebagai capres.
Namun lagi-lagi kita mesti berkaca kepada yang sudah-sudah. Selama dua periode pemerintahan SBY, sudah dua orang wapres yang berlatar belakang ekonom dan pengusaha. Angka pertumbuhan ekonomi memang cukup bagus. Perekonomian pun dinilai stabil, terutama jika dihadapkan pada krisis moneter 1997.
Namun demikian, masa Gus Dur dan Megawati, yang wapresnya tidak berasal dari kalangan teknokrat ternyata mampu membuat stabil ekonomi. Meski angka pertumbuhan tidak setinggi masa SBY, namun secara umum masalah ekonomi terkendali.
Keberadaan tim ekonomi yang dimiliki masa dua presiden tersebut, mampu memperbaiki permasalahan beban moneter dan perekonomian yang tengah morat-marit. Bahkan APBN yang defisit pun bisa diatasi. Tahun 2001-2004, pemerintah mampu mengupayakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,6 persen. Masa pemerintahan SBY, angka pertumbuhan ekonomi hanya 5,5 persen dalam kurun 2004-2009.
Jika dibandingkan, angka tersebut tidak jauh berbeda. Sebuah pencapaian yang bisa dibilang biasa saja. Apalagi faktor iklim perekonomian global yang telah kondusif kala itu, di tambah sektor swasta dalam negeri dan luar negeri yang semakin menggeliat, turut mendorong angka pertumbuhan terseebut.
Bahkan jika ditilik secara kritis, hadirnya wapres dari kalangan ekonom ternyata memberikan kesan semakin terbukanya praktik liberalisasi ekonomi. Jumlah privatisasi BUMN masa SBY ternyata lebih banyak dibandingkan masa sebelumnya.
Pada masa Megawati, alasan privatisasi beberapa BUMN adalah dalam kerangka untuk menutup hutang dan APBN yang defisit. Namun masa SBY, privatisasi terjadi justru pada saat APBN surplus. Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia melakukan privatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah kembali memprivatisasi 10 BUMN. Yang mengejutkan, di awal tahun 2008, pemerintah kembali mengumumkan privatisasi 34 BUMN, setelah sebelumnya juga meluncurkan 10 BUMN. Total privatisasi 44 BUMN dalam setahun, dengan dalih efisiensi.
Oleh karena itu kalangan ketiga berpikiran, cawapres yang tepat untuk Jokowi berasal kalangan yang kuat komitmennya dalam penegakan hukum. Terkait dengan hal ini, ada yang menarik dari pernyataan Kwik Kian Gie, seorang ekonom ternama dan pernah menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2003.
Menurutnya, dalam kondisi defisit APBN, ratusan triliun uang negara yang seharusnya dapat disetorkan ke kas negara, hilang akibat mental korup birokrat. Oleh karena itu Kwik menggarisbawahi bahwa pemberantasan KKN menjadi hal yang krusial bagi pemerintah. Dalam penilainnya, negara serta pemerintah tidak akan berdaya apa-apa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika praktik KKN masih menggerogoti negeri ini.
Dalam pendekatan analisis risiko, permasalahan seperti diplomasi yang lemah, optimalisasi potensi ekonomi Indonesia dan soal-soal turunannya, memang menjadi ancaman dan tantangan bagi Indonesia ke depan. Namun jika direfleksikan secara lebih jernih dan tenang maka apa yang diungkapkan Kwik Kian Gie memang benar adanya. Setidaknya ini bisa dijelaskan oleh dua hal.
Pertama, demokrasi di Negara manapun selalu membutuhkan hukum sebagai supremasi tertingginya. Absennya hukum sebagai supremasi selama ini telah membuat berbagai praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi banal. Demokrasi kehilangan nilai etiknya.
Kedua, korupsi hingga detik ini masih menjadi praktik yang semakin canggih dan hampir dimaklumi oleh nalar kehidupan bangsa kita. Praktiknya sudah tidak lagi terpusat di Jakarta melainkan menyebar seiring kebijakan otonomi daerah. Bahkan kehadiran KPK belum mampu menumpas penyakit laten itu secara tuntas. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan gerakan nasional untuk memeranginya. Di sini, kehadiran seorang pendamping yang memiliki latar belakang hukum bagi calon presiden seperti Jokowi, menemukan signifikansinya.
Panglima perang melawan korupsi
Selama hampir 16 tahun reformasi bergulir, baru tiga tuntutan yang dapat terealisasi, yaitu amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Tinggal pemberantasan korupsi inilah yang belum bisa optimal dilakukan oleh pemerintahan manapun.
Otonomi daerah menjadi hilang makna saat korupsi merajalela. Amandemen konstitusi menjadi sia-sia saat korupsi menjadi penyakit bangsa.
Rilis terakhir Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia mendapat skor 32, dengan peringkat 114 dari 177 negara. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan China. Dibanding dengan negara ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei dan Malaysia, sedikit di bawah Filipina dan Thailand, namun sedikit lebih baik dari Vietnam, Timor Leste, Laos dan Burma.
Korupsi merupakan tantangan nasional dan juga tuntutan reformasi yang mesti dijawab oleh Jokowi kurun masa kampanye ini. Dan menggandeng cawapres dari kalangan penegak hukum adalah sebuah langkah awal dan nyata yang ditunjukkan oleh seorang capres untuk menyambut tantangan nasional terbesar.
Dari berbagai data kita bisa dapatkan dampak buruk dari korupsi. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.
Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar. Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin.
Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Korupsi Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur. Korupsi juga menurunkan pendapatan pajak. Dan masih banyak lagi sederet dampak buruk dari kejahatan laten dan penyakit bagi bangsa ini.
Sebagai capres, Jokowi tentu menyadari atmosfer serta harapan masyarakat Indonesia ini. Rakyat tentu tidak ingin mengulang sejarah, dan tahun ini Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoreksinya dengan komitmen penuh pada penegakan hukum.
Alangkah indahnya jika bersama cawapres yang berlatar belakang hukum ini Jokowi bisa saling mengisi, layaknya dwitunggal Soekarno-Hatta. Namun jika harapan semacam itu terlalu tinggi maka cukuplah pasangan Jokowi dan cawapresnya menjadi pasangan yang memiliki pemilahan tugas yang jelas dan kompak bekerja sama. Jadikan agenda memerangi korupsi sebagai agenda nasional dan jadikan wapres sebagai panglimanya!
20 April 2014
