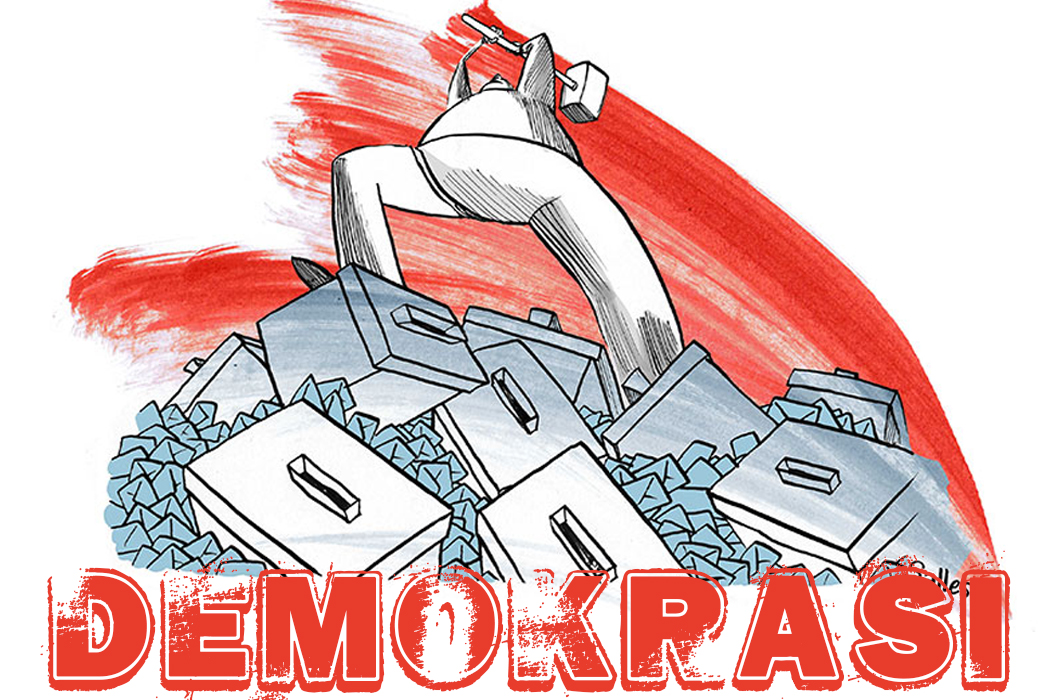
Efek Samping Demokrasi Kita
Reformasi ‘98 telah membawa corak demokrasi Indonesia yang berbeda dengan periode-
periode sebelumnya. Tidak saja terhadap model di masa Orde Baru yang hampir totaliter
namun juga terhadap model pasca Kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Demokrasi kita
bahkan mengalami dialektika yang luar biasa dengan berbagai eksperimentasi zig-zagnya.
Kita ingat bagaimana untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, sebuah pertanggungjawaban
presiden ditolak oleh MPR. Setelah itu, lebih dramatis lagi. Seorang Presiden RI dimakzulkan
lewat Sidang Istimewa MPR setelah tarik ulur politik yang tak menemukan titik kompromi.
Selanjutnya, sejak tahun 2004, kita mulai menganut demokrasi langsung. Selain anggota
DPR, seorang presiden dan kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. UUD 1945
mengalami amandemen, bahkan hingga lima kali. Hasilnya hampir merombak total tatanan
demokrasi sebelumnya. Lahir Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, hingga
sejumlah komisi negara. Bersamaan dengan itu, kita mulai mengenal corak politik baru:
politik pencitraan. Muncul pendekatan baru dalam politik, yakni politik kuantitatif yang
menitikberatkan pada angka keterpilihan seorang kandidat. Kemunculan lembaga-lembaga
survei dan konsultan politik menjadi keniscayaan berikutnya.
Hampir satu dekade corak politik ini bertahan untuk kemudian berubah bersamaan dengan
munculnya corak baru yang menjadi antitesisnya. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan
“politik prestasi” (best practice).
Kemunculannya ditandai dengan lahirnya seorang kepala daerah yang memiliki rekam jejak
dan prestasi kerja yang dinilai cukup kinclong. Kala itu, sepak terjang seorang Wali Kota Solo
tiba-tiba menjadi buah bibir dan pembicaraan orang se-Indonesia. Saat dia maju dalam
Pilgub DKI tahun 2012 dan berhasil memenangkannya, namanya semakin berkibar dan kali
ini warga dunia yang memperbincangkannya. Seolah tak terbendung, sosoknya bahkan
disebut sebagai salah satu orang berpengaruh di dunia ketika ia berhasil memenangkan dua
kali pilpres yang diikutinya. Kita tentu tahu siapa sosok yang dimaksud.
Seperti sudah menjadi hukum kehidupan, corak politik yang dibawanya pun kemudian
melahirkan antitesisnya. Namun kali ini cukup menguras tensi dan emosi bangsa. Karena
muskil untuk melawannya dengan cara konvensional maka dibutuhkan “ramuan” khusus
agar mampu melumpuhkan supremasi yang dipegangnya. Dan seperti yang kita tahu dan
lalui kemudian, politik identitas adalah jawabannya.
Sayangnya, politik identitas yang tersaji bukanlah yang banyak termaktub dalam teori-teori
politik pada galibnya, melainkan politik identitas yang didasarkan pada energi negatif dan
bahkan destruktif: dusta dan fitnah. Aktornya bukan tokoh politik resmi melainkan opinion
leader informal. Yang disasar juga bukan keberpihakan melainkan sentimen dan emosi
massa. Isu yang dipakai pun luar biasa riskan: SARA. Parpol yang berkepentingan hanya
mendompleng dalam rangka kepentingan elektoral. Akhirnya, selain tidak rasional, politik
indentitas yang berlangsung juga tidak memiliki alamat yang jelas. Berbeda dengan praktik
di luar.
Di AS, kampanye American First dan gugatan terhadap keberadaan kaum imigran jelas
disampaikan oleh Donald Trump, sang presiden terpilih. Di Perancis, seruan yang kurang
lebih sama juga jelas aktornya, Marine Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional. Demikian
juga di Belanda dengan sosok Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda. Lalu di
Italia ada Partai League, Partai Rakyat di Denmark, dan Partai Alternatif untuk Jerman di
Jerman. Semua kampanye mereka senafas: menjadikan identitas sebagai isu utama ideologi
mereka. Dan yang paling penting, aktor politiknya jelas.
Berbeda dengan di sini. Semua partai dan politisi mengaku Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal
Ika, menjunjung tinggi konstitusi, namun diam-diam bermain api dengan kelompok-
kelompok intoleran dan destruktif. Yang marak diterima publik kemudian justru semburan
dusta, bukan sikap politik yang mencerdaskan bangsa. Impaknya, polarisasi sosial hingga
ancaman disintegrasi menganga di depan mata.
Kenyataan ini telah menjadi bagian dari “efek samping” dalam dialektika demokrasi kita
selama lebih dari dua dekade Reformasi. Kecenderungannya juga eskalatif. Sejak kita
mengenal demokrasi langsung kala itu juga kita mulai mengenal money politics. Praktiknya
bahkan semakin banal dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Kesadaran politik
rakyat rusak dibuatnya. Jalan pikiran warga jadi pragmatis, transaksional, dan egois. Jauh
dari filosofi agung gotong-royong. Etika dan kepatutan politik menipis. Keteladanan dari elit
pun menjadi barang mahal dan langka. Dan ketika caci maki, fitnah beserta dusta menjadi
amunisi utama dalam politik, kiranya, itulah efek terparah dari demokrasi yang kita jalani
sejauh ini.
Memang, di satu sisi, Pilpres 2019 memperlihatkan kepada kita bagaimana angka partisipasi
warga begitu tinggi – hingga di atas 80 persen. Keberpihakan mereka terhadap para calon
presiden benar-benar murni. Bahkan politik uang disebut tidak mampu membobolnya.
Namun sayang, keberpihakan itu tidak terbangun di atas nalar yang sehat. Yang ada justru
sentimen dan bahkan nalar kebencian. Akhirnya, politik yang semestinya melahirkan
keadaban publik malah menjadi manifestasi dari dekadennya perilaku kita.
Jika diibaratkan sebagai mobil, demokrasi kita hari ini mungkin sudah sekelas Rolls-Royce.
Namun sayangnya ia berjalan di jalan yang penuh lubang. Sopirnya pun baru belajar dan
tidak tahu manual penggunaannya. Para penumpangnya juga awam dan gagap dengan
segala kemewahan yang ada di dalamnya. Dan dengan mobil itu, kita sebenarnya hanya
ingin pamer dan sok disebut maju dan modern agar dipandang hebat dan dipuji oleh pihak
luar. Dus, jalannya mobil yang super mewah itupun menjadi ugal-ugalan. Ia tidak
menghasilkan sebuah perjalanan yang mengesankan dan tidak mampu mengantarkan pada
tujuan yang telah ditetapkan. Alih-alih membuat nyaman, mobil yang kita kendarai malah
membuat porak poranda sebuah perkampungan.
Melihat semua kenyataan itu rasanya tidak cukup jika proses demokrasi kita dihampiri
dengan sekadar kritik dan evaluasi belaka. Dengan biaya yang tidak sedikit dan begitu
besarnya nilai yang dipertaruhkan, sudah saatnya kita berefleksi akan paham dan praktik
demokrasi kita sejauh ini. Momen pasca Pemilu 2019 yang telah begitu menguras energi
bangsa dengan berbagai prahara dan korban jiwa, kiranya menjadi momentum yang tepat
untuk hal ini.
Karena yang diperlukan adalah refleksi maka ia butuh pertanyaan-pertanyaan yang lebih
mendasar. Misalnya; kira-kira sudah di jalan yang benarkah demokrasi kita? Semakin
sehatkah demokrasi kita, atau ia hanya banyak membuka ruang kebebasan saja tanpa
kedewasaan para pelakunya? Seberapa kompatibel sebenarnya bangsa ini dengan
demokrasi langsung? Jika kompatibel, di titik mana mis atau erornya? Seberapa salah kita
menurunkan derajat MPR? Dan seberapa benar kita menghapus GBHN? Benarkah kita harus
kembali pada “Demokrasi Pancasila”? Mundurkah kita jika mewacanakan soal ini kembali?
Perlukah demokrasi Indonesia disetel ulang ke factory setting-nya? Atau yang dibutuhkan
sekadar modifikasi ulang saja? Dst.
Semua pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk mengajak kita kembali ke (atau
beromantisme dengan) masa lalu. Ini juga bukan sikap skeptis atas demokrasi itu sendiri.
Namun sebuah refleksi memang selalu membutuhkan renungan-renungan mendalam guna
menemukan kesalahan-kesalahan mendasar untuk kemudian kita perbaiki bersama.
Bukankah orang-orang agung mengajarkan itu?
Willy Aditya
*Anggota DPR RI, Ketua DPP Partai NasDem
